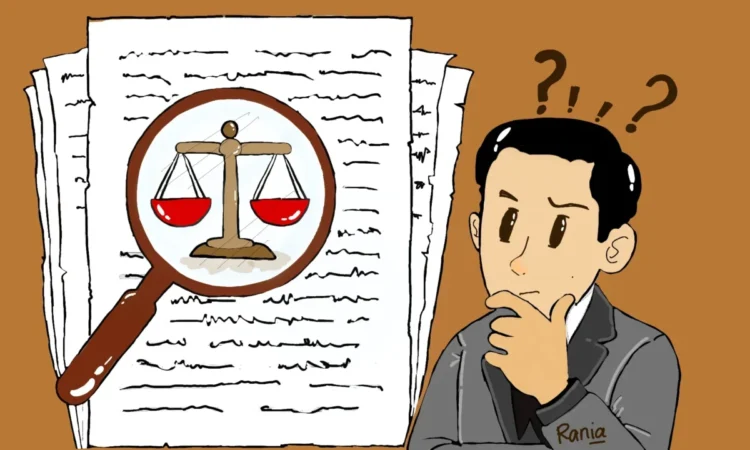Oleh: Nia Rahmayuni*
Putusan terhadap Thomas Trikasih Lembong, mantan Menteri Perdagangan yang dikenal luas sebagai Tom Lembong, menuai perhatian besar. Bukan hanya karena vonis hukuman penjara 4 tahun 6 bulan dan denda Rp750 juta atas perkara dugaan korupsi dalam penerbitan izin impor gula, tetapi juga karena tebalnya dokumen putusan yang mencapai lebih dari seribu halaman. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah keadilan memang harus serumit itu?
Dalam sidang pembacaan vonis pada 18 Juli 2025 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini terdiri atas lebih dari seribu halaman. Karena terlalu panjang, hakim hanya membacakan pokok-pokok isi putusan dan mengabaikan bagian dakwaan, tuntutan jaksa, pleidoi kuasa hukum, serta keterangan saksi. Ini dilakukan dengan asumsi bahwa semua pihak di ruang sidang telah memahami proses yang berlangsung.
Namun, keputusan untuk tidak membacakan keseluruhan isi dokumen putusan justru mengundang polemik. Publik bertanya-tanya apakah putusan sepanjang itu benar-benar menunjukkan kedalaman dan ketelitian hukum, atau justru menjadi bentuk eksklusi yang mengaburkan kejelasan dan transparansi?
Hakim bahkan menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya niat jahat (mens rea) dalam tindakan Tom Lembong. Ini memunculkan pertanyaan kritis, apakah yang sedang diadili adalah kesalahan administratif dalam pengambilan keputusan, atau motif kriminal yang merugikan negara?
Jaksa sebelumnya menuntut hukuman penjara 7 tahun dan denda Rp750 juta, dengan tambahan 6 bulan kurungan jika denda tidak dibayar. Negara disebut mengalami kerugian hingga Rp578,1 miliar karena rekomendasi impor gula yang dikeluarkan Lembong saat menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Namun, dalam persidangan, Lembong membela diri dengan menyatakan bahwa tindakannya dilakukan dalam kapasitas resmi untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Ia menegaskan bahwa tidak ada kepentingan pribadi dalam kebijakan tersebut.
Dilansir dari Hukumonline, fakta persidangan juga menunjukkan bahwa Lembong tidak menikmati keuntungan dari kebijakan tersebut dan tidak terbukti memiliki niat jahat. Ia mengaku mengeluarkan rekomendasi secara terbuka dan administratif. Namun, jaksa tetap menganggapnya sebagai tindakan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.
Masalahnya, dalam birokrasi Indonesia yang sering kali tumpang tindih dan multitafsir, batas antara kesalahan administratif dan pelanggaran pidana kerap kabur. Pejabat publik bisa tersandung hukum karena keputusan yang mereka ambil demi kepentingan umum dianggap tidak sesuai prosedur. Maka muncul pertanyaan yang lebih dalam apakah negara sedang menghukum sebuah kebijakan, atau menghukum seseorang karena posisi strategisnya?
Ironisnya, putusan setebal lebih dari seribu halaman itu tidak mudah diakses oleh publik. Bahkan media massa tidak mampu mengulasnya secara menyeluruh karena kompleksitas bahasa hukum yang digunakan. Hal ini berisiko menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Sebab, dalam masyarakat demokratis, keadilan tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus dapat dilihat dan dipahami oleh masyarakat.
Dikutip dari Inilah.com, pakar hukum pidana Universitas Bung Karno, Hudi Yusuf, menilai bahwa proses hukum terhadap Lembong menunjukkan adanya ketimpangan. Ia menyebutnya sebagai “kriminalisasi terhadap individu yang menjalankan perintah sistem,” sementara aktor yang diduga lebih berperan tidak tersentuh hukum. Jika pernyataan ini benar, maka peradilan tidak lagi menjadi ruang penegakan keadilan, tetapi panggung politik yang menyesatkan.
Sebagaimana ditegaskan dalam pandangan hukum progresif, keadilan seharusnya tidak hanya hadir dalam bentuk formal melalui prosedur hukum, tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat. Putusan hukum yang adil adalah putusan yang bisa dipahami oleh mereka yang terdampak, yakni masyarakat luas. Karena pada akhirnya, keadilan bukan diukur dari jumlah halaman dokumen, tetapi dari kejelasan, keterbukaan, dan rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh publik.
Seribu halaman putusan tidak akan berarti apa-apa jika isinya tidak dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Publik tidak membutuhkan ribuan halaman untuk percaya pada keadilan. Yang mereka butuhkan adalah penjelasan yang masuk akal, transparan, dan tidak terkesan menyembunyikan kebenaran di balik kerumitan bahasa hukum. Karena keadilan sejati bukanlah milik segelintir ahli, melainkan hak seluruh rakyat.
*Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu budaya, Universitas Andalas