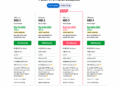Oleh: Asyani Rahayu Simatupang

Menjadi jurnalis di Indonesia tidak pernah mudah. Tekanan politik, ancaman hukum, hingga kekerasan fisik adalah bagian dari risiko yang harus dihadapi dalam profesi ini. Namun, bagi jurnalis perempuan, tantangannya jauh lebih besar. Selain menghadapi risiko yang sama dengan rekan laki-laki mereka, jurnalis perempuan juga menjadi sasaran pelecehan, intimidasi berbasis gender, hingga serangan brutal yang mengancam nyawa. Kasus demi kasus menunjukkan bahwa masih banyak pihak yang ingin membungkam suara perempuan di media, terutama mereka yang berani mengungkap kebenaran yang tidak nyaman bagi penguasa atau kelompok berkepentingan.
Salah satu bukti nyata betapa seriusnya ancaman terhadap jurnalis perempuan adalah teror yang diterima Tempo pada 19 Maret 2025. Sebuah kepala babi dengan kedua telinga terpotong ditemukan di kantor redaksi mereka, sebuah pesan mengerikan yang ditujukan kepada Francisca Christy Rosana, jurnalis yang juga host siniar Bocor Alus Politik. Ancaman ini bukan hanya sekadar aksi teror fisik, tetapi juga serangan psikologis yang bertujuan menanamkan ketakutan. Ini adalah strategi lama yang digunakan untuk membungkam kebebasan pers: menyerang individu agar mereka dan rekan-rekannya takut untuk terus berbicara.
Selain itu, contoh nyata ketimpangan gender dalam dunia jurnalisme adalah kasus Febriana Firdaus, jurnalis investigasi yang kerap menghadapi ancaman akibat liputannya mengenai hak asasi manusia dan isu minoritas. Saat bekerja di Tempo dan meliput kasus penganiayaan yang dialami Tama Satria Langkun dari Indonesian Corruption Watch (ICW), ia diancam oleh pelaku hingga terpaksa menginap di kantor Tempo demi keselamatannya. Pada tahun 2019, Febriana menjadi korban doxing, di mana informasi pribadinya disebarluaskan di internet, memicu ancaman serius terhadap dirinya dan memaksanya menunda beberapa investigasi terkait situasi konflik di Papua. Selain itu, ia juga pernah mengalami peretasan akun media sosial dan surel, yang semakin memperlihatkan betapa rentannya jurnalis perempuan terhadap serangan digital. Ancaman terhadapnya mencerminkan bagaimana kebebasan pers di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama bagi jurnalis yang meliput isu-isu sensitif.
Kasus ini bukanlah insiden yang berdiri sendiri. Sepanjang tahun 2024, Aliansi jurnalis independen (AJI) indonesia mencatat 73 kasus kekerasan terhadap jurnalois, dengan 20 diantaranya berupa kekerasan fisik dan satu kasus pembunuhan jurnalis. Lebih kanjut, survei yang dilakukan oleh AJI dan PR2Media (Wendratama et al., 2023) selama september hingga oktober 2022 terhadap 852 jurnalis perempuan dari 34 provinsi mengungkap bahwa 82,6 persen responden pernah mengalami kekerasan seksual, 80,8 persen pernah mengalami pelecehan seksual sepanjang karier jurnalistik mereka. Jenis kekerasan yang paling banyak dialami meliputy body shaming secara luring (58,9%), catcalling secara luring (51,4%), dan body shaming secara daring (48,6%)
Fakta ini menunjukkan bahwa budaya woman-hating masih kuat mengakar di masyarakat. Jurnalis perempuan yang vokal dianggap menyalahi norma sosial dan harus dihukum, bukan melalui argumen yang sehat, tetapi dengan ancaman yang brutal. Dalam banyak kasus, respons publik pun sering kali tidak berpihak pada korban. Alih-alih menuntut keadilan bagi jurnalis yang diintimidasi, sebagian masyarakat justru mempertanyakan mengapa mereka terlalu berani atau terlalu vokal. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan yang berbicara di ruang publik masih kerap diperlakukan sebagai ancaman, bukan sebagai bagian dari demokrasi yang sehat.
Tidak hanya itu, dunia media sendiri masih menghadapi masalah ketimpangan gender yang membuat jurnalis perempuan lebih rentan terhadap serangan. Survei yang dilakukan oleh PR2Media dalam kurun waktu september hingga oktober 2022, menemukan bahwa 232 dari 852 responden (27,2%) pernah menerima pesan teks atau audiovisual dengan muatan seksual eksplisit, seperti gambar alat vital, video pornografi, atau pesan ajakan hubungan seksual. Selain itu, 41 responden mengaku pernah dipaksa memenuhi keinginan seksual pelaku, termasuk menyentuh organ intim. Lebih tragis lagi, 22 responden melaporkan bahwa mereka pernah mengalami pemerkosaan.
Meski jumlah jurnalis perempuan semakin meningkat, mereka masih menghadapi bias diskriminasi di ruang redaksi. Diskriminasi ini mencakup berbagai aspek, seperti promosi jabatan, upah yang tidak setara, dan kurangnya perlindungan saat menghadapi ancaman. Selain itu, dari 852 responden, 57,2 responden menyatakan kantor mereka belum memiliki prosedur standar operasi (SOP) untuk menangani kasus kekerasan seksual, sehingga korban sering kali tidak mendapatkan dukungan memadai. Dalam banyak kasus, ketika jurnalis perempuan melaporkan ancaman atau pelecehan yang mereka terima, respons dari perusahaan media justru cenderung menyalahkan korban atau meminta mereka ”lebih berhati hati”
Padahal, peran jurnalis dalam demokrasi sangatlah vital. Jimly Asshiddique, ketua mahkamah konstitusi (MK) dalam sebuah acara yang digaagas oleh aliansi jurnalis independen (AJI) dan ikatan jurnalis televisi indonesia (ITJI) menegaskan bahwa pers adalah pilar keempat demokrasi. Kebebbasan pers telah dijami dan diakui keberadaannya oleh UUD 1945, Sejajar dengan tiga pilar demokrasi lainnya, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini juga diperkuat oleh undang undang no 40 tahun 1999 tentang pers, yang menegaskan bahwa kemerdekaan pers adalah hak yang dilindungi hukum, dan swegala kekerasan atau upaya menghambat kerja jurnalis adalah pelanggaran serius terhadap prinsip demoikrasi. Artinya, serangan terhadap jurnalis bukan hanya pelanggaran terhadap individu, tetapi juga ancaman serius terhadap sistem demokrasi itu sendiri.
Upaya mitigasi kekerasan terhadap jurnalis perempuan harus menjadi agenda bersama. Jurnalis perempuan, sebagai penyintas, juga dapat berperan sebagai aktivis dengan berani berbagi pengalaman serta berkolaborasi dalam menanggulangi kekerasan yang mereka alami. Perusahaan pers, organisasi jurnalis, dan masyarakat sipil dapat menggalakkan kampanye serta advokasi hukum, sekaligus menciptakan ruang kerja yang lebih kondusif bagi perempuan. Selain itu, Dewan Pers dapat merumuskan kebijakan terobosan yang mendorong penyelesaian struktural dan kultural untuk mengatasi budaya kekerasan terhadap jurnalis yang terus meningkat (Masduki et al., 2021).
Jika intimidasi terhadap jurnalis dibiarkan tanpa konsekuensi, maka yang kita hadapi bukan sekadar ancaman terhadap individu, tetapi ancaman terhadap demokrasi itu sendiri. Karena pada akhirnya, kebebasan pers adalah benteng terakhir yang memastikan suara rakyat tetap terdengar.
Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.