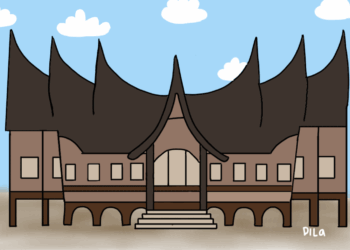Oleh: Nasywa Luthfiyyah Edfa*
Beberapa waktu yang lalu viral di internet kisah Dedi Hermawan, seorang guru di SDN VI Sumberpetung, Dusun Pondok Kobong, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, yang mengajar satu orang murid di ruang kelas yang sempit. Di balik kisah dedikasi tersebut, tersembunyi persoalan yang jauh lebih besar, yakni ketimpangan pendidikan antara kota dan desa.
Kondisi SDN VI Sumberpetung menunjukkan bahwa ketimpangan itu masih nyata. Sekolah ini memiliki ruang kelas yang sangat terbatas. Beberapa ruang belajar bahkan harus digabung dan hanya dipisahkan oleh triplek tipis. Ruang belajar jauh dari standar, dengan ukuran sempit, fasilitas minim, serta keterbatasan sarana pendukung yang sudah menjadi keseharian siswa dan guru.
Di sisi lain, sekolah-sekolah di wilayah perkotaan tumbuh dengan sarana dan prasarana yang lengkap. Dua kondisi ini berada dalam satu sistem pendidikan yang sama, namun dijalankan dengan realitas yang sangat timpang. Kenyataan tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan di Indonesia belum benar-benar berdiri di titik yang setara. Akses dan fasilitas masih menjadi faktor penentu besar kecilnya kesempatan seorang anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Kondisi SDN VI Sumberpetung yang kini hanya memiliki satu murid di kelas V, yakni Ilham Mahendra, tentu tidak terjadi tanpa sebab. Fenomena ini berkaitan dengan keputusan banyak orang tua yang memindahkan anak-anak mereka ke sekolah lain yang dianggap memiliki fasilitas lebih baik. Urbanisasi juga mendorong perpindahan itu, ketika sekolah-sekolah di perkotaan menawarkan sarana pendidikan yang lebih lengkap dan dianggap lebih menjanjikan.
Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan tidak hanya soal gedung dan fasilitas, tetapi juga berkaitan dengan pola pikir dan pilihan masyarakat yang semakin condong ke kota, meninggalkan ruang-ruang belajar di pelosok dalam sunyi. Media kerap menyoroti kisah heroik guru-guru yang mengajar di tengah keterbatasan. Sosok pahlawan tanpa jasa dipuja karena ketulusan dan pengorbanannya. Namun, di balik narasi heroik tersebut, peran negara justru kerap luput dari sorotan. Pertanyaan mendasarnya adalah di mana tanggung jawab negara?
Padahal, UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 Ayat (4) bahkan mengamanatkan negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Ironisnya, di banyak daerah terpencil, amanat konstitusi ini belum sepenuhnya dirasakan. Ketika ketulusan guru menjadi wajah utama pendidikan di pelosok, kegagalan struktural justru semakin tak terlihat. Keterbatasan fasilitas, distribusi sekolah yang tidak merata, serta minimnya perhatian terhadap sekolah-sekolah kecil seolah tertutup oleh slogan pengabdian tanpa batas.
Di lapangan, guru memikul beban berlapis. Mereka bukan hanya pendidik, tetapi juga motivator agar siswa tidak berhenti sekolah, sekaligus penjaga terakhir agar sekolah tidak benar-benar punah. Dalam situasi ini, guru dipaksa menjadi pahlawan, sementara tanggung jawab negara semakin kabur.
Di balik perhatian publik terhadap pengorbanan guru, ada satu pihak yang kerap terlupakan, yaitu anak itu sendiri. Ilham, satu-satunya murid kelas V, harus menjalani proses belajar tanpa teman sebaya. Ia belajar sendirian, tanpa ruang untuk berdiskusi, bercanda, atau berkompetisi sebagaimana pengalaman anak-anak pada umumnya.
Sekolah sejatinya bukan hanya ruang akademik, tetapi juga ruang sosial untuk membangun kepercayaan diri, empati, dan keterampilan berkomunikasi. Ketika ruang sosial itu hilang, yang terjadi bukan sekadar kekurangan teman bermain, melainkan kehilangan bagian penting dari proses tumbuh kembang anak. Ilham menghadapi apa yang bisa disebut sebagai kesepian akademik, belajar tanpa dinamika sosial yang semestinya menyertai pendidikan.
Minimnya interaksi juga menghilangkan kompetisi yang sehat. Tidak ada perbandingan kemampuan, tidak ada saling memotivasi, dan tidak ada proses belajar dari teman sebaya. Padahal, persaingan yang sehat kerap menjadi pemicu semangat belajar dan pembentukan karakter.
Lebih jauh, kondisi ini berpotensi menghambat perkembangan sosial dan emosional anak. Anak bisa tumbuh dengan rasa terisolasi dan kesulitan beradaptasi ketika kelak berada di lingkungan yang lebih besar. Ketimpangan pendidikan, dalam konteks ini, tidak lagi sekadar soal fasilitas, tetapi telah menyentuh masa depan psikologis dan sosial seorang anak.
Ironisnya, situasi seperti ini sering dianggap sebagai nasib anak-anak di daerah terpencil. Negara hadir lebih sebagai penonton ketulusan guru, bukan sebagai penjamin hak anak. Padahal, setiap anak memiliki hak yang sama atas pendidikan yang layak dan sehat secara sosial. Kisah Ilham seharusnya menjadi cermin bahwa ketimpangan pendidikan bukan hanya memisahkan desa dan kota dari segi akses, tetapi juga dari pengalaman masa kecil yang utuh sebagai pelajar. Jika kondisi ini terus dibiarkan, yang dikorbankan bukan sekadar satu sekolah kecil, melainkan masa depan satu generasi secara perlahan.
Kisah seorang anak yang belajar sendirian di ruang kelas tidak seharusnya berhenti sebagai cerita viral sesaat. Ia adalah potret nyata tentang bagaimana negara masih abai memastikan pendidikan yang adil. Selama ketimpangan dianggap wajar, pendidikan akan terus menjadi hak istimewa, bukan hak dasar yang benar-benar dijamin bagi semua.
*Penulis Merupakan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas