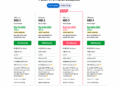Oleh: Pitri Yani*
Di tepi Danau Maninjau yang bening, diapit oleh lembah dan bukit yang diselimuti kabut, berdirilah sebuah rumah panggung sederhana. Rumah panggung yang menjadi saksi bisu perjalanan seorang ulama besar sekaligus sastrawan Indonesia, Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau yang lebih dikenal dengan Buya Hamka. Dari rumah inilah kisah panjang itu berawal. Kisah seorang anak kampung yang kelak menjelma menjadi cendekiawan dan tokoh bangsa, yang pemikirannya menembus batas negeri hingga ke tanah seberang.
Kini, rumah itu dirawat oleh generasi penerusnya. Di balik dinding kayu yang tua, tersimpan kenangan akan masa kecil sang ulama. “Buya Hamka itu anaknya ada dua belas, dan saya anak yang paling bungsu,” ujar Amir Syakib, putra bungsu Hamka, saat ditemui Genta Andalas pada Minggu (26/10/2025). Suaranya mengandung kebanggaan sekaligus rindu, seolah setiap hembusan angin danau membawa kembali bayangan ayahnya di masa kecil.
Sejak kecil, Hamka dikenal cerdas sekaligus keras kepala. Ia menimba ilmu agama di Sumatera Thawalib Padang Panjang, pesantren yang didirikan ayahnya, Haji Abdul Karim Amrullah, ulama besar pembaharu Islam di Minangkabau. Namun, ikatan darah justru membuat hubungan keduanya sering bergesekan. “Karena yang punya pesantren itu ayahnya sendiri, Hamka sering kabur dan pulang ke kampung. Akhirnya, ia dijemput kembali oleh sang ayah dan dipindahkan ke pesantren di Parabek, Bukittinggi,” ujar Syakib.
Namun di balik kenakalan itu, bersemayam jiwa pembelajar yang tak pernah padam. Di usia 15 tahun, Hamka dikirim ke Pulau Jawa untuk menimba ilmu yang lebih luas. Lima tahun kemudian, ia menikah dengan Siti Raham, seorang gadis Mandailing. Pernikahan itu kemudian dipercepat untuk melindungi Siti Raham dari kekacauan masa pendudukan Jepang.
Tak lama kemudian, pasangan muda itu merantau ke Medan, tanah yang menjadi saksi metamorfosis Hamka dari pengembara menjadi sastrawan. Dari ruang kecil di rumahnya, ia menulis karya-karya yang menggetarkan jiwa: Merantau ke Deli, Di Bawah Lindungan Ka’bah, dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijck. Karya-karya itu lahir dari pengamatannya terhadap kehidupan sosial dan batin manusia. Ia menulis bukan sekadar dengan pena, tapi dengan hatinya.
Dari Medan, perjalanan membawanya ke Jakarta atas permintaan Presiden Soekarno. Di ibu kota, Hamka membantu membangun Masjid Al-Azhar dan kemudian diangkat sebagai imam besar. Namun takdir seolah ingin mengujinya lebih jauh. Fitnah politik di masa itu menyeretnya ke penjara, atas tuduhan hendak menggulingkan pemerintah dengan bantuan Malaysia.
Bagi keluarga, masa itu adalah luka yang tak mudah disembuhkan. Buku-buku karya Hamka dibakar, harta benda disita, dan ancaman kekerasan menghantui setiap malam. Tapi dari balik jeruji, Hamka menyalakan lentera maaf yang tak padam.
Ketika kekuasaan beralih dan Soekarno jatuh, sebuah surat datang ke tangannya. “Wahai sahabatku Hamka, maafkan aku,” tulis Soekarno, “Aku telah menzalimimu. Jika aku meninggal, hanya engkaulah yang boleh mensalatkan jenazahku.” Dan Hamka, dalam balasan yang penuh ketulusan hati, menulis, “Wahai sahabatku Soekarno, kau tidak bersalah. Kau termakan fitnah komunis. Dendam tak kubawa mati, musuh tak kubawa pulang. Selangkah tapakku keluar rumah, kau sudah kumaafkan.” Kalimat itu bukan sekadar balasan surat, melainkan cermin keluhuran budi seorang ulama yang menempatkan kasih di atas dendam.
Setelah wafatnya pada 1981, rumah kelahirannya di Maninjau sempat terbengkalai. Bahkan, di masa pendudukan Jepang, rumah itu pernah dihancurkan ketika mereka memburu ayah Hamka. Hingga akhirnya, bantuan datang dari negeri jiran “Datanglah tamu dari Malaysia, yang sekarang menjadi Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Katanya, mereka dari Perserikatan Angkatan Belia Islam Malaysia ingin bersilaturahmi dengan keluarga Buya Hamka,” ujar Syakib.
Dari pertemuan itulah lahir gagasan membangun kembali rumah kelahiran sang ulama. Tahun 2000, Museum Rumah Kelahiran Buya Hamka akhirnya berdiri di tepi Danau Maninjau. Barang-barang pribadi, tongkat, serta buku-buku peninggalannya dibawa dari Jakarta untuk melengkapi museum itu. “Malaysia merasa berutang budi pada Hamka karena beliau pernah menenangkan hubungan Indonesia dan Malaysia di masa genting. Bahkan Anwar Ibrahim sampai merasa seperti anaknya sendiri.” Ujar Syakib.
Sebagian besar karya Hamka berakar pada pergulatan antara adat dan agama. Perang batin yang telah ia kenal sejak kecil. Tenggelamnya Kapal Van der Wijck, misalnya, bukan sekadar kisah cinta yang tragis, tapi juga kritik terhadap adat yang membelenggu.
Konflik itu sesungguhnya juga hidup dalam dirinya sendiri. Ayahnya dikenal kera sementara Hamka lebih terbuka terhadap perubahan. Namun, pada akhirnya, kedua tokoh besar itu berdamai di ujung hayat. Kini, setiap hari pengunjung datang ke rumah kecil itu dari berbagai kota, bahkan dari Malaysia. Tidak ada tiket masuk, hanya sebuah kotak amal kecil untuk menjaga listrik dan air tetap menyala. Di mata Amir Syakib, menjaga rumah itu bukan sekadar kewajiban, tetapi bentuk bakti kepada sejarah.
Buya Hamka bukan sekadar nama di buku sejarah. Ia adalah cahaya yang menuntun di antara kabut zaman. Seorang ulama yang menjembatani cinta, adat, dan kemanusiaan. Dan di tepi Danau Maninjau yang hening itu, gema perjuangannya masih terdengar, lembut tapi abadi.
*Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas