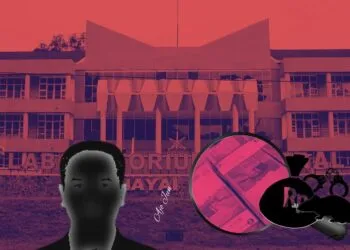Oleh: Zahra Nurul Aulia
Media sosial adalah pisau bermata dua, di satu sisi memberikan akses informasi dan edukasi, tetapi di sisi lain berdampak negatif pada penggunaan yang tidak terkontrol. Konten yang hanya berorientasi pada hiburan instan membuat otak terbiasa dengan stimulus cepat tanpa tantangan untuk berpikir secara mendalam.
Brain rot adalah salah satu istilah yang tak asing pada era digital sekarang ini. Istilah ini didefinisikan sebagai kemerosotan fungsi otak yang diduga terjadi pada kondisi mental atau intelektual seseorang akibat konsumsi berlebihan terhadap konten daring.
Istilah brain rot menjadi semakin populer di platform media sosial, terutama di kalangan Gen Z dan Gen Alpha. Bahkan dalam laman Oxford University Press, istilah brain rot dinobatkan sebagai istilah terpopuler, melibatkan 37.000 orang responden. Hal ini menggambarkan kekhawatiran terhadap dampak konsumsi konten daring berkualitas rendah yang berlebihan, yang dapat merusak kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan dunia nyata, karena masyarakat menghindari pemikiran mendalam dan lebih memilih hal-hal yang dangkal.
Penggunaan istilah ini dalam budaya daring menjadi lebih spesifik, sering kali dengan nuansa lucu, merendahkan diri, dan humoris di kalangan penggunanya. Misalnya, serial video viral “Skibidi Toilet” karya Alexey Gerasimov yang menampilkan toilet humanoid, meme “hanya di Ohio” yang menggambarkan kejadian-kejadian aneh di Ohio, meme Jokes Homok (Jomok) yang merujuk pada lelucon atau kata-kata lucu yang ditujukan pada pria yang terlihat seperti gay, serta meme viral yang menampilkan karakter-karakter tidak normal dengan nama yang menirukan aksen Italia.
Konten-konten ini memunculkan “bahasa brain rot” dengan contoh kata seperti “skibidi” untuk sesuatu yang tidak masuk akal, dan “Ohio” untuk sesuatu yang memalukan atau ganjil, yang menunjukkan bagaimana tren bahasa dari budaya daring yang viral bisa menyebar ke kehidupan nyata.
Brain rot tidak hanya merusak interaksi nyata seseorang, tetapi juga berdampak pada kualitas pemikiran dan kesehatan mental secara keseluruhan. Penggunaan media sosial yang berlebihan membuat seseorang menjadi malas berpikir kritis, lebih memilih hal-hal yang mudah dan instan untuk menghindari masalah. Hal ini menandakan penurunan daya mental dan intelektual di era evolusi digital.
Bentuk lain dari brain rot adalah zombie scrolling, dampak dari kecanduan ponsel, yang didefinisikan sebagai kegiatan menggulir media sosial tanpa tujuan atau manfaat yang nyata. Terjebak dalam dunia digital tanpa mengenal waktu, dengan mata lesu, kulit pucat pasi, dan jari yang aktif menggulir ponsel, sementara pikiran sebagian besar tidak berfungsi dan fokus hanya pada gambar bergerak cepat di layar.
Berawal dari depresi, kecemasan sosial, perasaan terisolasi, rendah diri, dan merasa kesepian, para zombie scroller begadang hingga larut malam karena tidak dapat berhenti menggeser layar. Efek jangka panjang dari kecanduan ponsel ditambah kurang tidur berdampak serius pada kesehatan mental dan fisik seseorang.
Di kalangan pelajar, penggunaan gawai yang berlebihan dan ketergantungan pada konten tidak bermutu dapat memengaruhi cara mereka menyelesaikan tugas sekolah yang dianggap terlalu berat. Perilaku menunda-nunda menjadi wajar akibat penurunan daya pikir dan kemampuan berpikir kritis. Remaja yang terlalu sering mengakses konten instan, seperti video pendek TikTok atau Instagram Reels, mengalami kesulitan mempertahankan fokus pada tugas kompleks, sehingga mudah terdistraksi dan mudah lupa.
Mengutip dari newportinstitute.com, Dr. Grant, seorang psikolog media yang diakui secara internasional dengan keahlian khusus dalam dampak teknologi pada kesehatan mental, menggunakan frasa “bandingkan dan putus asa” untuk menggambarkan perbandingan sosial negatif yang dilakukan orang dewasa muda saat menelusuri aplikasi. Penelitian Facebook sendiri menemukan bahwa Instagram—yang digunakan oleh 71 persen orang dewasa muda menurut Pew Research Center—berdampak negatif pada kesehatan mental. Gambar-gambar “sempurna” yang dikurasi di aplikasi tersebut menimbulkan perasaan iri dan rendah diri.
Dr. Grant menyebut ini sebagai “dorongan organik untuk terhubung.” Sindrom zombie scrolling, selain menimbulkan emosi negatif, juga mencegah kita terlibat dalam pengalaman positif di dunia nyata, di mana peluang untuk interaksi dan emosi positif terjadi sepanjang waktu, tetapi tidak kita sadari karena lebih terpaku pada ponsel.
Hal ini terwujud dalam bentuk ketegangan mata, kelelahan otak (dikenal sebagai brain rot), kesulitan fokus, perasaan terputus secara emosional, dan gejala kecanduan ponsel lainnya, bahkan saat kita telah berhenti menggulir layar.
Siklus kecanduan ponsel berdampak pada kesehatan mental: kurang tidur dikaitkan dengan harga diri rendah, kemampuan menyelesaikan masalah yang menurun, dan prestasi akademis yang buruk. Selain itu, kualitas tidur yang buruk juga dikaitkan dengan perilaku berisiko tinggi seperti penggunaan narkoba atau alkohol, dan menyakiti diri sendiri.
Pada akhirnya, cara untuk menghentikan zombie scrolling adalah menggantinya dengan perilaku yang mendukung perkembangan diri. Misalnya: menumbuhkan kebiasaan perawatan diri yang sehat, berolahraga, melakukan pekerjaan yang bermakna dan menginspirasi, serta menjalin komunikasi aktif di dunia nyata.
Dengan membatasi waktu penggunaan media sosial—tidak lebih dari dua jam untuk anak-anak dan maksimal empat jam untuk orang dewasa per hari (di luar pekerjaan)—serta memilih konten berkualitas dari sumber terpercaya, membaca artikel dan buku literasi, melakukan refleksi terhadap informasi yang diterima, mengurangi konten yang hanya menawarkan hiburan instan, dan lebih banyak berinteraksi secara langsung dengan keluarga dan teman, menjadi langkah nyata untuk menghindari dampak negatif yang lebih buruk ke depannya.
Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Andalas